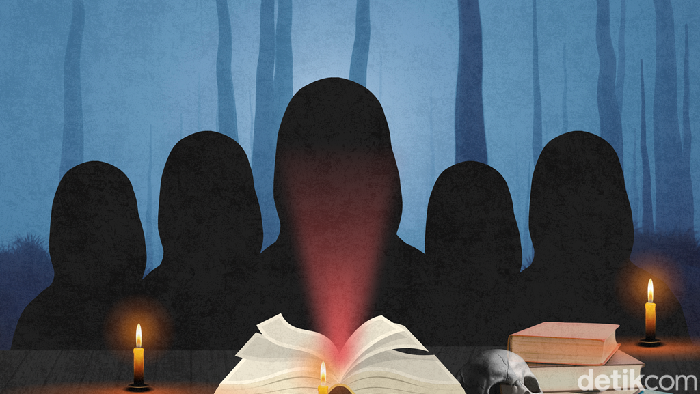Dalam lintasan sejarah sosial-keagamaan Sukabumi, terdapat satu nama yang sempat mencuat dan mengundang kontroversi pada dekade 1960-an hingga 1970-an. Ia adalah Moehammad Isa, yang lebih dikenal dengan nama Isa Bugis, seorang pendakwah yang mendirikan lembaga pendidikan keagamaan bernama Pembaru di Sukabumi.
Nama “Isa Bugis” memang kerap menimbulkan salah tafsir. Menurut Rangga Suria Danuningrat, pegiat sejarah dari Soekaboemi History, nama “Bugis” yang melekat pada dirinya bukan berasal dari Suku Bugis di Sulawesi Selatan, melainkan diduga karena perubahan pelafalan dari kata “Buge” tempat asal Isa di Aceh, tepatnya di Lhok Buge, Lhokseumawe.
“Dalam versi lain yang dimuat di Majalah Gatra edisi 3 Desember 2016, Isa Bugis disebut lahir di Pidie, Aceh pada 1926. Namun beberapa sumber menyebutkan ia berasal dari Lhok Buge. Nama Bugis disematkan karena orang Padang, tempat ia sempat mengenyam pendidikan, sulit menyebut ‘Buge’ sehingga berubah menjadi ‘Bugis’,” ujar Rangga kepada infoJabar, Selasa (8/4/2025).
Setelah menamatkan pendidikan menengah di Aceh, Isa hijrah ke Jakarta untuk melanjutkan studi di Universitas Islam Jakarta, meski tak selesai. Beberapa catatan lain menyebutkan bahwa ia pernah belajar di perguruan tinggi Islam di Yogyakarta dan Jawa Timur. Namun nama kampusnya tidak pernah disebut secara pasti.
Di masa mudanya, Isa Bugis aktif dalam berbagai gerakan keislaman. Ia sempat bergabung dengan Laskar Mujahidin Aceh saat usianya masih 21 tahun, sebuah laskar pejuang Islam yang mirip dengan Hisbullah dan Sabilillah di Pulau Jawa. Kemudian ia tercatat bergabung dengan Gerakan Pemuda Islam Indonesia, organisasi underbow Partai Masyumi, sekitar tahun 1955. Ia bahkan disebut pernah menjadi perhatian tokoh nasional seperti Mohammad Natsir.
Setelah Pemilu 1955, di mana suara Masyumi kalah dari Partai Nasional Indonesia dan Partai Komunis Indonesia, para elite partai melakukan evaluasi. Isa Bugis termasuk yang dilibatkan dalam tim diskusi internal. Di sinilah ia menyampaikan kritik tajam soal kesalahan sistematika perjuangan politik Islam dalam tubuh Masyumi.
“Setelah perdebatan panjang, Isa Bugis memilih keluar dari Masyumi dan bekerja di Djawatan Agama Jakarta pada 1963. Tak lama kemudian ia mundur dan menjadi pedagang kelontong sambil berdakwah secara independen di Jakarta, Tangerang, hingga ke Sukabumi,” terang Rangga.
Kehadiran ajaran Isa Bugis di Sukabumi pada awal 1960-an tak bisa dilepaskan dari dinamika sosial dan keagamaan masyarakat setempat yang tengah mengalami transformasi pasca-pergolakan DI/TII Kartosuwiryo.
“Pascapenumpasan DI/TII, masyarakat Sukabumi berada dalam fase pencarian dan kehati-hatian. Mereka butuh pendekatan baru terhadap agama yang tak lagi dikaitkan dengan kekerasan,” ungkap Rangga.
Wilayah Sukabumi kala itu masih dihantui trauma konflik ideologi Islam bersenjata. Di tengah ketidakpastian dan kebutuhan spiritual yang mendalam, ajaran Isa Bugis yang mengusung pendekatan rasional terhadap Al-Qur’an serta terbuka terhadap siapa pun, menjadi alternatif yang memikat.
“Orang datang ke pengajian Isa Bugis bukan karena militansi, tapi karena penasaran akan cara baru memahami agama. Apalagi bentuknya mirip akademi yang bertahap, bukan pesantren konvensional,” jelasnya.
Dalam perjalanan dakwahnya, Isa Bugis mendirikan lembaga pendidikan bernama Akademi Ummat Pembina Masyarakat Baru, yang disingkat Ummat Pembaru, di Sukabumi pada 28 Agustus 1963.
“Beberapa sumber menyebut Pembaru ini merupakan peleburan dari yayasan dakwah yang pernah berdiri di Cibadak dan Jakarta. Nama ‘Pembaru’ sendiri merujuk pada pendekatan mereka yang berbeda dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam,” jelas Rangga, mengutip data dari buku Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia (1989) dan arsip LPPI.
Ajaran Isa Bugis disusun secara sistematis dalam tiga tahap pengajaran. Tahap pertama adalah persiapan, yang membahas penciptaan alam, manusia, dan kehidupan, disampaikan dalam sembilan pertemuan. Tahap kedua disebut dasar, membahas hakikat hidup dalam 13 kali pertemuan. Tahap ketiga tidak dibatasi waktu, berisi kajian Al-Qur’an baik dari sisi sastra maupun makna mendalam.
Secara penampilan, pengikut Isa Bugis tidak berbeda jauh dari umat Islam pada umumnya. Tidak ada kewajiban berjilbab atau berjanggut panjang. Bahkan, kelompok ini tergolong inklusif dan tidak menutup diri terhadap pendatang baru.
Namun seiring waktu, ajaran Isa Bugis mulai menuai kritik. Ia dituding meremehkan kisah-kisah dalam Al-Qur’an seperti Nabi Musa dan Nabi Ibrahim yang dianggapnya sebagai dongeng belaka. Ia juga menyebut air zamzam sebagai “air bekas bangkai orang Arab” dan menganggap semua tafsir Al-Qur’an yang ada sudah ketinggalan zaman.
“Akibat ajaran-ajarannya yang dianggap melenceng, Orde Baru melalui Kodim 0607 Sukabumi mengeluarkan larangan terhadap kegiatan Isa Bugis. Termasuk pelarangan ceramah dan dakwah oleh mahasiswa Pembaru,” tutur Rangga.
Departemen Agama turut turun tangan. Melalui proyek pengawasan terhadap aliran kepercayaan, peneliti Amin Djamaluddin menyimpulkan bahwa gerakan Isa Bugis terpengaruh faham kiri dan memiliki simpati terhadap Partai Baath di Irak. Hasil penelitian ini memperkuat persepsi bahwa ajaran Pembaru adalah ancaman ideologis.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Puncaknya, pada 22 Oktober 1968, PAKEM Jawa Barat menerbitkan surat keputusan bernomor B-8302/Kep/PAKEM/1968 yang secara resmi melarang seluruh kegiatan penyebaran dan pengamalan ajaran Isa Bugis. Larangan ini dikeluarkan bersamaan dengan beberapa kelompok lain seperti Darul Hadits dan Jamaah Qur’an Hadits.
Merasa terpojok, para pengikut Isa Bugis akhirnya membubarkan kegiatan Pembaru di Sukabumi. Sebagian besar dari mereka memilih hijrah ke Lampung. Dalam narasi mereka, perpindahan itu dianggap sebagai bentuk hijrah seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah.
Rangga menjelaskan, dalam tulisannya Afif Hm menekankan bahwa pada prinsipnya Isa Bugis ingin menghadirkan reformasi dalam pemahaman Islam, baik dalam pendekatan tafsir maupun pelaksanaan ajaran dalam kehidupan empiris umat. Namun ajaran itu tak mampu bertahan dari tekanan politik dan pandangan keagamaan arus utama.
“Saat ini, ajaran Isa Bugis tinggal jejak dalam dokumen dan ingatan para saksi sejarah. Namun dari situlah kita bisa belajar bagaimana dinamika keagamaan, interpretasi ajaran, serta intervensi negara membentuk arah sejarah lokal seperti di Sukabumi,” tutup Rangga.